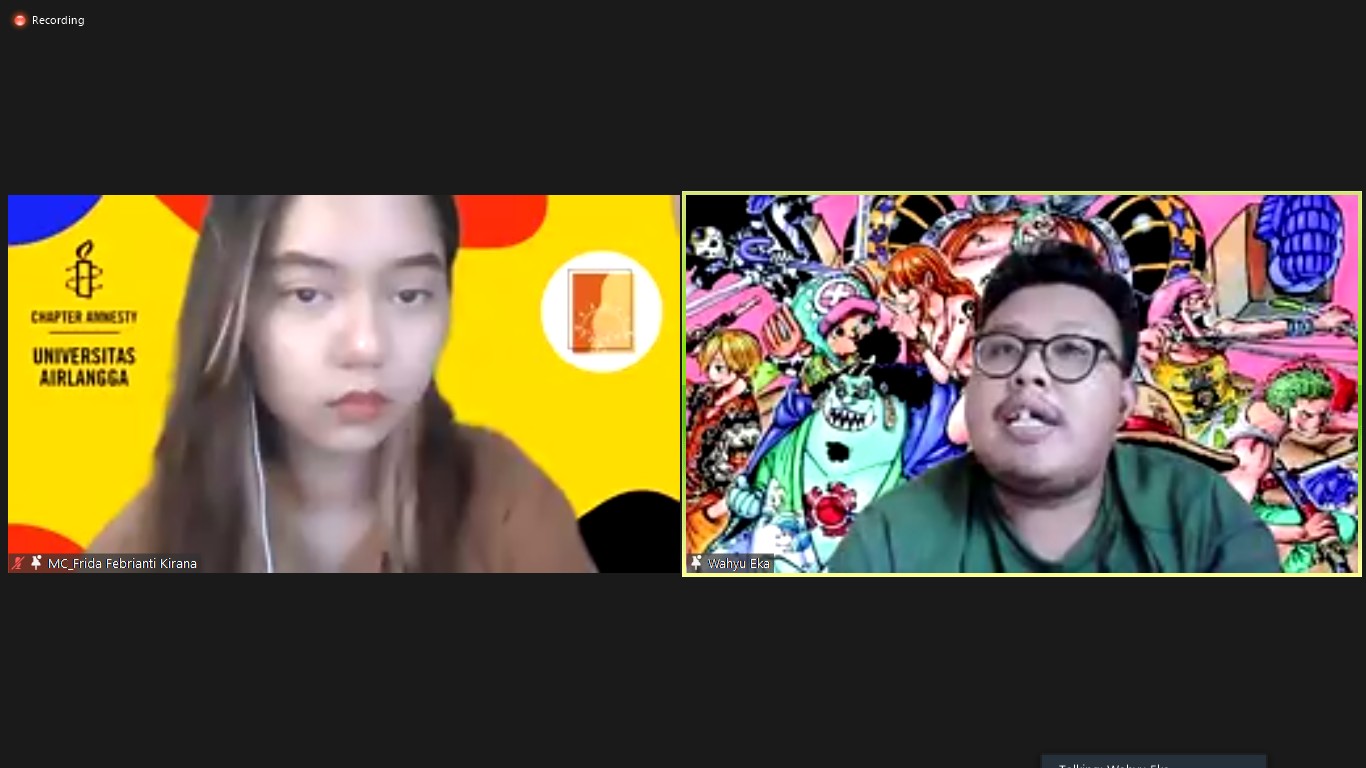UNAIR NEWS – Dalam rangka memperingati International Plastic Bag Free Day, Komite Hak Lingkungan Amnesty International Indonesia Chapter UNAIR mengadakan webinar pada Minggu pagi (4/7/2021) yang mengangkat tema “Ancaman Mikroplastik dan Hak Asasi yang Dilanggar”. Narasumber terakhir yang diundang pada perhelatan itu adalah Manager Kampanye WALHI Jatim Wahyu Eka Setyawan.
Menyadur data dari KLHK RI, Wahyu bertutur bahwa jumlah sampah yang ada di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 68 juta ton, dengan 9,52 juta ton. Jumlah ini tak hanya mencakup sampah lokal, tetapi sampah impor yang acapkali digunakan untuk industri kertas. Wahyu menambahkan bahwa bisnis impor sampah ini dilakukan tanpa implementasi regulasi yang ketat, sehingga memperparah krisis sampah yang ada di Indonesia.
“Seakan-akan Indonesia ini menjadi tempat sampah untuk negara-negara maju dengan embel-embel bisnis impor. Padahal, terdapat penelitian Ecoton yang mengatakan bahwa 35% dari impor sampah tersebut merupakan sampah plastik yang destruktif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujar alumni Fakultas Psikologi UNAIR itu.
Wahyu mengatakan bahwa kehadiran plastik untuk mempermudah dan mempermurah keberlangsungan hidup manusia, terutama dalam konteks produksi dan konsumsi produk, pada akhirnya menimbulkan pola konsumerisme yang destruktif. Hegemoni kapitalisme menurut aktivis lingkungan itu berkontribusi dalam krisis plastik ini. Masyarakat terbiasa (terkadang juga terpaksa) untuk membeli produk tertentu yang berbahan plastik atau tidak ramah lingkungan, tetapi di satu sisi masyarakat juga dibombardir oleh gaung kewajiban untuk melestarikan lingkungan. Jadi terdapat suatu kontradiksi.
Wahyu menelaah pola konsumerisme itu menggunakan teori relasi produksi Karl Marx. Dominansi kapitalisme dalam masyarakat pada akhirnya akan mewajibkan konsumen untuk menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-harinya untuk bertahan hidup. Padahal, pesan bahwa penggunaan plastik itu berbahaya bagi lingkungan sudah dipahami publik secara meluas. Namun masyarakat akan tetap menggunakan plastik sekalipun itu tidak menguntungkan bagi lingkungan (dalam jangka panjang juga merugikan manusia), karena alternatif pola hidup yang tak berbasis plastik itu hampir tidak mungkin bagi masyarakat pada umumnya.
“Sedihnya lagi, industri kapitalis yang berkontribusi besar pada penggunungan sampah plastik itu acapkali menerapkan taktik pemasaran yakni green washing. Disini, nilai hijau atau nilai ramah lingkungan dalam produksi suatu produk dikomodifikasi,” ujar dosen luar biasa FPsi UNAIR itu.
Greenwashing biasanya memasarkan suatu produk dengan cara bahwa produk ini menggunakan bahan yang ramah lingkungan, atau penjualan produk ini akan berkontribusi pada reboisasi hutan. Anggota WALHI itu bertutur bahwa sejatinya greenwashing merupakan penipuan publik yang dilakukan oleh industri kapitalis agar dapat tetap terwujud elongasi profit. Tak hanya itu, greenwashing seringkali diinkorporasi oleh korporasi yang sebelumnya telah dikecam publik karena tidak ramah lingkungan, sehingga persepsi publik mereka dapat terrestorasi dan terjadi maksimalisasi persepsi legitimasi atas tindakan-tindakan mereka yang sejatinya tetap merusak lingkungan. Wahyu menambahkan bahwa greenwashing mendistraksi konsumen dari kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan melalui pola hidup yang eco-friendly, menjadi terjerembap pada perilaku konsumeristik atas dasar keramahan lingkungan yang palsu.
“Apabila alur produksi sampah plastik diabstraksikan, itu merupakan suatu siklus. Bahan baku plastik merupakan minyak bumi yang diestraksi dari bumi. Pada akhirnya setelah plastik selesai diproduksi dan dimanfaatkan dalam aktivitas manusia, pada akhirnya akan dibuang kembali ke ekosistem. Konstruksi sosial dan legal saat ini masih minim memperkirakan penghitungan dampak dari pembuangan tersebut,” papar Wahyu.
Untuk itu, Wahyu mengatakan bahwa perlu adanya bingkai hukum dan kebijakan yang ekosentris, tak hanya antroposentris saja. Hal ini diperuntukkan untuk mengembalikan peran dan siklus alam menjadi sebagaimana mestinya yang sebelumnya retak akibat aktivitas industri. Hukum ekologi ini harus didasari oleh pemahaman bahwa perilaku manusia itu selalu terkoneksi dengan alam, kepekaan terhadap apa yang kita buang kepada alam, serta aktivitas ekonomi harus peka terhadap dampak lingkungannya.
Penulis: Pradnya Wicaksana
Editor: Nuri Hermawan