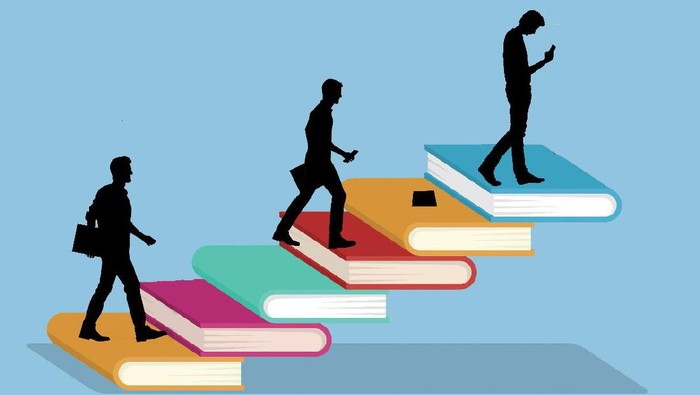Institusi pendidikan idealnya menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya pertemuan berbagai perbedaan dan media untuk menjalin relasi sosial tanpa harus dibayang-bayangi syakwasangka. Tetapi, dalam kenyataan tidak sedikit institusi pendidikan ternyata justru menjadi wadah bagi persemaian sikap intoleransi dan bahkan paham radikalisme yang makin meresahkan. Institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat belajar-mengajar yang netral dari sikap intoleransi, justru dalam kenyataan menjadi lembaga yang rawan terkontaminasi pengaruh negatif sikap intoleransi dan radikalisme.
Berbagai studi telah banyak memperlihatkan bagaimana benih-benih persemaian sikap intoleran bahkan radikalisme ternyata mulai tumbuh ketika siswa masuk ke sekolah di jenjang SMP maupun SMA. Studi yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian I(LaKIP) (2010) dari Oktober 2010 hingga Januari 2011 tentang tingkat intoleransi dan radikalisme di kalangan guru Pendidikan Agama Islam dan para pelajar di wilayah Jabodetabek menemukan bentuk intoleransi yang berkembang terlihat dari kesediaan responden melakukan sejumlah tindakan, seperti pengrusakan dan penyegelan rumah ibadah bermasalah (guru 24,5%, siswa 41,1%), pengrusakan rumah atau fasilitas anggota keagamaan sesat (guru 22,7%, siswa 51,3%), pengrusakan tempat hiburan malam (guru 28,1%, siswa 58,0%), atau pembelaan dengan senjata terhadap umat Islam dari ancaman agama lain (32,4%, siswa 43,3%). Sebanyak 23,8% guru setuju terhadap ide dan tindakan tokoh-tokoh radikal, sementara siswa 13,4%. Studi yang dilakukan Farcha Ciciek di tujuh kota (Jember, Padang, Jakarta, Pandeglang, Cianjur, Cilacap dan Yogyakarta) menemukan hal yang sama, yakni sekitar 13% siswa mendukung gerakan radikal dan 14% setuju dengan aksi terorisme.
Studi yang penulis lakukan dan telah mewawancarai 500 pelajar dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur menemukan indikasi yang kurang-lebih sama. Meski pun di kalangan pelajar mereka telah menyadari arti penting multikulturallisme, tetapi dalam praktik mereka seringkali bersikap ambivalensi. Pada tataran konstruksi, sebagian besar siswa sebetulnya sudah menyadari bahwa keberagaman dan toleransi adalah prasyarat dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang memang pluralistik. Namun demikian, sebagian besar siswa umumnya lebih mempertimbangkan keselamatan diri sendiri daripada ikut campur dalam urusan persekusi yang mereka saksikan di sekolah. Sebagian besar siswa mengaku akan membela jika ada teman mereka yang menjadi korban persekusi atau tindakan intoleransi. Namun demikian, dalam kenyataan mereka umumnya masih menimbang berbagai faktor dan implikasi dari tindakannya.
Dari segi jumlah, tindakan intoleransi yang dilakukan pelajar barangkali belum terlalu besar. Tetapi, sekitar 20-25% pelajar yang bersikap intoleran dan bersimpati kepada gerakan radikalisme, sesungguhnya adalah benih-benih yang kontra-produktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak mustahil terjadi, akibat peran sebagian guru (agama) yang seolah mendukung intoleransi, dalam kenyataan makin mendorong tumbuhnya sikap intoleransi di kalangan pelajar. Dari hasil wawancara mendalam diketahui sebagian pelajar merasa apa yang mereka lakukan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut, sehingga berikap mengambil jarak dan bahkan melakukan persekusi kepada kelompok yang berbeda dianggap wajar dilakukan.
Dalam suasana dan latar belakang kehidupan politik yang panas tatkala Pilkada DKI Jakarta dan Pemilu berlangsung, masyarakat –tak terkecuali para pelajar—memang sebagian sikap mereka cenderung terbelah dalam dua kubu. Satu kelompok yang lebih mengidentifikasi sebagai representasi kelompok Islam dan pribumi, sedangkan kelompok yang lain ditempatkan sebagai representasi kelompok Islam Liberal atau Abangan, dan pembela kelompok Aseng (non-pribumi). Kelompok yang dinilai merepresentasikan kelompok Aseng dan Islam liberal, mereka biasanya cenderung lebih berpotensi menjadi korban persekusi dan bullying teman di sekolah.
Studi yang dilakukan di lima kota/kabupaten di Jawa Timur ini menemukan bahwa cukup banyak siswa yang enggan atau merasa tidak perlu memberi ucapan Selamat Merayakan Hari Natal kepada teman mereka yang merupakan umat Nasrani karena dianggap melanggar Akidah. Lingkungan pergaulan, proses sosialisasi dan habitus yang menjadi tempat siswa tumbuh-kembang umumnya mendukung perkembangan sikap intoleransi di kalangan sebagian siswa. Tidak hanya sosialisasi orang tua, tetapi penjelasan guru agama di sekolah juga seringkali mendorong siswa untuk mengambil jarak dengan kelompok yang berbeda (the olther), terutama ketika mereka harus memilih memberi ucapan Selamat Hari Natal atau tidak.
Mengembangkan sikap toleransi di kalangan siswa, harus diakui memang bukan hal yang mudah. Adanya perbedaan sosial dan posisi satu kelompok kecil yang minoritas sering melahirkan tindakan diskriminatif dan bullying. Studi yang dilakukan Parker (2017) tentang kelompok perempuan muslim minoritas di Bali menemukan siswa perempuan muslim di Bali umumnya mereka dikonstruksikan untuk merasa inferior oleh orang Bali, dan merasa malu saat menggunakan jilbab. Jilbab menandai mereka sebagai kelompok yang inferior, sehingga sebagian merasa minder (inferior, kurang percaya diri, dan rendahan). Status sosio-ekonomi yang rendah di kalangan pendatang – diasosiasikan dengan kemiskinan, pendidikan rendah, pekerja kasar dan ketidakamanan ekonomi. Remaja putri muslim yang merasa malu saat menggunakan hijab karena merasa minder dan diasingkan oleh orang Bali sebagian besar karena merepresentasikan kasus klasik tentang bawahan yang diasingkan –yang merupakan budaya yang dibawa dominan mayoritas.
Studi yang dilakukan Hoon (2014) di sekolah Kristen Jakarta menemukan hal yang sama. Meski sekolah telah berupaya untuk mengembangkan nilai-nilai yang menghargai keberagaman dan toleransi, tetapi karena para orang tua yang bersikap apatis dan para siswa yang dikepompongi oleh etnis dan agama mereka sendiri, menyebabkan ‘muslim pribumi’ selalu menjadi subjek penghinaan dan demonisasi. Lingkungan eksklusif juga berkontibusi dalam mempertahankan batasan rasial. Walaupun beberapa guru menunjukkan upaya menjanjikan dalam penanaman toleransi beragama, desakan sekolah yang mengharuskan murid non-Kristen untuk berpartisipasi dalam aktivitas agama Kristen dan intoleransi pada mnoritas seksual menunjukkan standar ganda. Hoon (2014) menyatakan peran pendidikan orang tua dan kelas sosio-ekonomi adalah sentral dari perkembangan habitus toleransi dan habitus disiplin. Bagi umat Kristen, sekolah adalah tempat untuk mengembangkan reflektif kritis dan sikap penghargaan terhadap perbedaan. Batasan toleransi harus selalu di (re)negosiasi agar toleransi tidak hanya dibatasi pada sempitnya interpretasi agama. Untuk mengintegrasi para siswa ke dalam masyarakat multikultural Indonesia yang lebih luas, sekolah membutuhkan keseimbangan antara memepertahankan identitas agama dan mempromosikan nilai pluralisme, toleransi dan penghormatan. Dari hasil studinya di Oman, Al Sadi, & Basit (2013) menyimpulkan pendidikan yang menekankan persamaan antar agama terbukti mampu menekan intoleransi.
Perkembangan kondisi politik dan habitus sosial yang keliru sering melahirkan siswa yang sensitif dan mudah mengembangkan perilaku yang intoleran kepada sesamanya. Kunci untuk membangun sikap dan perilaku yang toleran kepada perbedaan adalah bagaimana sosialiasi dan lingkungan sosial mendukung ke arah itu (Johansson, 2008). Studi yang dilakukan Raihani (2014) di Palangkarya, Kalimantan Tengah menemukan para pelajar umumnya telah memiliki modal budaya yang didapat dari keragaman agama dan toleransi dari keluarga dan masyarakat, yang mana itu semua terbukti membantu mereka untuk menciptakan ‘budaya toleransi’ di sekolah. Meski Palangkaraya pernah dilanda kerusuhan etnis antara orang Dayak dengan pendatang Madura yang menjadi tragedi nasional dan terlepas pula dari kebijakan sekolah yang tidak konsisten terkait dengan keragaman agama, ternyata para pelajar memiliki cara tersendiri menyikapi perbedaan. Raihani (2014) menyatakan di sini guru agama memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman siswa tentang keragaman agama dan toleransi melalui pengajaran yang disengaja tentang beberapa aspek agama lain.
Rahma Sugihartati
Departemen IIP FISIP Universitas Airlangga
Versi lengkap artikel ini bisa dilihat pada: Rahma Sugihartati, Bagong Suyanto, Medhy Aginta Hidayat, Mun’im Sirry & Koko Srimulyo, Habitus of Institutional Education and Development in Intolerance Aattitude among Students, Talent Development & Excellence, Vol 12, No 1, 2020, 1965-1979.